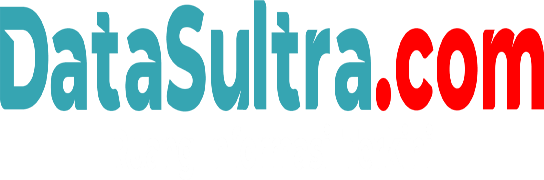Oleh: Nang Bagia / Kadek Yogiarta
Kendari, Datasultra.com – Saya membaca sebuah berita tentang Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Penguatan Kapasitas Stakeholder Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digelar di Hotel Claro Kendari pada Senin 4 Agustus 2025.
Dalam forum tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa terdapat 11 kawasan transmigrasi tersebar di 10 kabupaten, termasuk tiga kawasan prioritas nasional: Kawasan Mutiara (Kab. Muna), Asinua-Routa (Kab. Konawe), dan Anawua-Toari (Kab. Kolaka).
Sebagai anak dari keluarga transmigran asal Bali, saya menyambut kabar ini dengan rasa syukur dan harapan besar. Saya lahir dan dibesarkan di tanah transmigrasi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Tawamelewe yang kini telah mekar menjadi tiga desa, salah satunya Desa Tanggondipo, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.
Itu terjadi 42 tahun lalu, buah dari program transmigrasi yang diikuti kakek dan ayah saya pada tahun 1974, di masa ketika kehidupan masih sangat sulit.
Masa Kecil dalam Keterbatasan
Saya masih mengingat jelas bagaimana ibu saya (kami memanggilnya meme dalam bahasa Bali) memasak nasi dengan campuran ubi dan jagung karena beras sangat terbatas.
Demi saya, anak bungsunya yang masih kecil dan bosan dengan makanan campuran, ia selalu menyisihkan sedikit nasi putih yang kami sebut nasi oran. Kini, makanan sederhana itu justru saya rindukan karena di dalamnya tersimpan kisah ketulusan dan perjuangan.
Lahan transmigrasi kala itu belum sepenuhnya terbuka. Sawah di lahan kedua belum tergarap, sementara lahan pertama pun masih berupa ladang kering. Irigasi belum tersedia. Rumah-rumah papan beratap seng berdiri di atas tanah tanpa lantai semen.
Tidak ada listrik, dan untuk menyapa tetangga pun kami harus menembus semak belukar karena masing-masing keluarga mendapat jatah pekarangan seluas satu hektare.
Ayah dan kakek saya bekerja siang malam. Saya masih ingat kakek sering menyambangi masyarakat lokal demi menjalin hubungan baik, pulang membawa kelapa atau bahan kayu untuk membuat bajak sawah.
Semua harus dilakukan secara manual, mulai dari membajak dengan sapi, membangun irigasi dengan gotong royong, hingga membuka lahan secara swadaya. Saya sendiri, sejak tahun 90-an, sepulang sekolah ikut ke sawah membantu orang tua meratakan tanah. Semua demi membuka harapan baru menanam padi.
Dari Lahan Semak Menjadi Lumbung Pangan
Setengah abad telah berlalu. Kini, wilayah transmigrasi telah berubah secara signifikan. Jalanan beraspal, rumah-rumah permanen, listrik menjangkau desa-desa, dan anak-anak transmigran telah banyak yang meraih pendidikan tinggi, menjadi ASN, TNI, hingga Polri. Saya adalah generasi ketiga, dan saya bangga menyebut Sulawesi Tenggara sebagai tanah kelahiran saya.
Program transmigrasi membawa dampak positif bagi masyarakat lokal, khususnya dalam pengembangan pertanian. Pendatang dari Bali dan Jawa memperkenalkan teknik bercocok tanam yang sistematis, pola tanam bergilir, pengelolaan irigasi sederhana, hingga pengukuran tata lahan yang efisien.
Kini, kawasan yang dulu hanya hutan dan lahan tidur telah menjelma menjadi sentra pangan: padi, jagung, sayur-mayur, hingga komoditas hortikultura. Kabupaten Konawe, Kolaka Timur, hingga Bombana menjadi tulang punggung penyediaan pangan Sultra, sementara SP-trans di Muna Barat dikenal sebagai sentra penghasil buah.
Bukan Sekadar Pindah, Tapi Membangun Masa Depan
Transmigrasi bukan hanya soal perpindahan penduduk, tetapi rekayasa sosial yang berhasil menciptakan kolaborasi budaya antara pendatang dan masyarakat lokal. Terjadi pertukaran ilmu, pengalaman, pola kerja, hingga pembauran budaya yang memperkaya keberagaman Indonesia.
Di banyak tempat, lahir ikatan sosial yang harmonis, termasuk perkawinan lintas budaya yang memperkuat persatuan bangsa.
Namun tidak semua kisah transmigrasi berjalan mulus. Persoalan agraria kerap muncul, termasuk di desa saya sendiri. Selama tiga tahun lebih, konflik kepemilikan lahan antara warga lokal dan transmigran terjadi, membawa dampak sosial yang tidak ringan.
Beruntung, pada 21 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Konawe mengeluarkan maklumat resmi yang ditandatangani enam unsur pimpinan daerah, menyatakan bahwa konflik tersebut telah diselesaikan. Warga kini mendapat kembali kepastian hukum atas lahan mereka, meskipun masih ada kekhawatiran yang tersisa.
Pelajaran penting dari peristiwa ini: negara harus hadir, bukan hanya saat awal program, tetapi juga dalam proses dan penyelesaian masalah. Transmigrasi sebagai instrumen pemerataan pembangunan harus disertai dengan perlindungan hukum, jaminan hak atas tanah, serta pembinaan berkelanjutan.
Menatap Masa Depan: Transmigrasi yang Berkeadilan
Sulawesi Tenggara masih menyimpan banyak potensi. Lahan-lahan luas di wilayah pedalaman dan kepulauan menunggu untuk dikelola oleh tangan-tangan ulet dan kreatif.
Dengan pendekatan transmigrasi modern yang partisipatif, ekologis, dan berbasis budaya lokal saya yakin ekonomi daerah bisa tumbuh lebih pesat dan setara dengan daerah lain di Indonesia.
Saya menulis ini bukan hanya sebagai nostalgia, tetapi sebagai suara dari anak-anak transmigrasi yang telah menjadi bagian dari narasi pembangunan daerah.
Kami bukan pendatang yang “numpang hidup,” kami adalah warga yang ikut membangun, menanam, dan mencintai tanah ini. Dari ladang alang-alang kini berdiri sawah subur, rumah ibadah, sekolah, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat.
Saya percaya, dengan kerja keras, ketekunan, dan keberpihakan negara terhadap keadilan, program transmigrasi dapat kembali menjadi harapan bagi masa depan Indonesia yang merata, berdaya, dan sejahtera terutama di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara.
Penulis: Anak Transmigrasi yang Tinggal di Kota Kendari